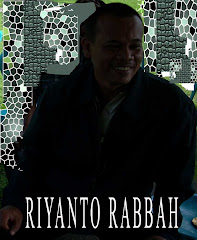PROFILE
 Sastrawan senior yang bernama lengkap I Gusti Putu Arya Tirtawirya ini lahir 10 Mei 1940 di Mataram, Nusa Tenggara Barat। Mengecimpungi penulisan verpen, esai, kritik sastra dan artikel budaya umum। Pun penulisan cerita anak-anak (dongeng) serta resensi buku. Karya-karyanya tersebar di aneka Koran dan majalah : Kompas, Karya Bhakti, Horison, Sastra, Tribun dan sebagainya.
Sastrawan senior yang bernama lengkap I Gusti Putu Arya Tirtawirya ini lahir 10 Mei 1940 di Mataram, Nusa Tenggara Barat। Mengecimpungi penulisan verpen, esai, kritik sastra dan artikel budaya umum। Pun penulisan cerita anak-anak (dongeng) serta resensi buku. Karya-karyanya tersebar di aneka Koran dan majalah : Kompas, Karya Bhakti, Horison, Sastra, Tribun dan sebagainya.Buku himpunan cerpennya : “Pasir Putih Pasir Laut”, “Malam Pengantin”, “Kegelapan di Bawah Matahari”, “Saat Kematian Semakin Akrab.”Buku himpunan esainya :”Apresiasi Puisi dan Prosa”, “Antologi Esai dan Kritik Sastra”.Sajak-sajaknya termuat dalam beberapa antologi :”Penyair Bali”, “Pilar-Pilar “ (bersama Diah Hadaning) dan dalam Buku “Saat Kematian Semakin Akrab,”dllnya.Buku cerita anak-anak pernah terbit dengan judul : “Pan Balangtamak”, “Pan Camplung”.
Cerpennya, “Orang Kaya” diterjemahkan dalam bahasa Jerman oleh Prof.Dr. R.Carle dan dimuat dalam majalah Merian yang terbit di Hamburg, Jerman Barat. Cerpen-cerpennya pun mengisi buku Antologi “Cerita Pendek Indonesia” dan “Jakarta, 30 Cerita Pendek Indonesia” (terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur Malaysia) keduanya di bawah editor Satyagrha Hoerip (Alm).
Dalam buku Kritik Sastra, Sebuah Antologi” ini tergambar dengan jelas bahwa wawasannya seputar kesusastraan sebagaimana tersimpul dalam esai-esainya.
ESAI
MAKNA SUATU KRITIK SASTRA
Oleh :
Putu Arya Tirtawirya
Seorang editor buku antologi prosa atau puisi memang punya wewenang menulis kritik sastra sebagai pelengkap buku tersebut, sejauh dirinya tidak mendiskreditkan karya yang dimuat sekaitan dengan kedudukannya selaku editor yang telah memilih karya-karya yang memang layak dimuat.
Pada hakekatnya makna suatu kritik sastra itu bersifat sangat relatif. Tidak ada seorang kritikus manapun yang bakal bersifat obyektif seratus prosen mengingat begitu banyaknya metode kritik sastra dalam bidang kesusastraan. Pendapat seorang kritikus tidaklah bersifat mutlak benar—apa yang ia tulis hanyalah sebatas buah pikirannya sesuai dengan salah satu metode yang ia gandrungi. Atas dasar inilah mengapa sering terjadi kasus : berapa orang kritikus bertengkar masalah nilai sebuah karya sastra tertentu. Suatu pertengkaran yang disebut polemik di mana tidak ada pakar sastra yang bakal mampu menjadi hakim atau minimal melerai alias mendamaikan perang pena tersebut.
Menguak karya-karya cerpen, novel dan puisi, pada hakekatnya kita mencoba mengungkap dunia misteri berhubung terdapat banyak aliran penulisan yang semuanya dapat disederhanakan menjadi tiga katagori : aliran bersifat transparan dan yang prismatis dan satu lagi yang bersifat silhuet/abstrak. Dengan kalimat lain : karya sastra itu tidaklah seragam. Berangkat dari kenyataan ini maka kita tak menjadi heran; bahwa pihak penyair ( Goenawan Mohamad, Sapardi Joko Damono misalnya ) yang kok tidak mampu menjelasterangkan isi dari sajak-sajak yang digubahnya. “Apa gunanya saya menulis puisi apabila isinya dapat diuraikan secara prosais !” cetus Goenawan Mohamad dalam salah satu esainya. Begitu pula halnya cerpen, secara garis besar terdapat tiga aliran sesuai dengan gaya perintisnya masing-masing : Anton Chekov, Guy de Maupassant dan Franz Kafka.
Meskipun makna suatu kritik sastra relatif sifatnya, kehadiran kritisi sastra adalah penting : para penyair dan pengarang memperoleh hikmah dari kritik sastra yang mereka tulis, berkenaan dengan perkayaan wawasan seputar penciptaan karya sastra, paling tidak para sastrawan dilecut kesadarannya untuk memahami teori sastra maupun sejarah perkembangan kesusastraan dunia sehingga bakat alam yang dimiliki akan bergandengan dengan intelektualisme. Dua komponen yang seyogianya digenggam oleh seseorang yang berpredikat penyair atau pengarang. Berkat pemilikan intelek selaku intelektual maka seseorang di samping menciptakan karya sastra, masing-masing nantinya bakal mampu pula nimbrung dalam polemik dalam bingkai upaya meletakan suatu masalah pada proporsinya yang benar. Atas dasar inilah mengapa dalam bidang kritik sastra hadir isitilah “kritik atas kritik” : suatu pembelaan diri yang positif dari pihak penyair/pengarang yang buah karyanya dikritik baik secara langsung maupun tak langsung.
Sedangkan di dalam buku antologi cerpen terhimpun sejumlah cerpen yang masing-masing punya keunikan tersendiri dan ditopang oleh gaya bercerita (style) yang cukup memikat sesuai dengan tuntutan karya prosa : mengarang fiksi adalah suatu seni bercerita
MAKNA SUATU KRITIK SASTRA
Oleh :
Putu Arya Tirtawirya
Seorang editor buku antologi prosa atau puisi memang punya wewenang menulis kritik sastra sebagai pelengkap buku tersebut, sejauh dirinya tidak mendiskreditkan karya yang dimuat sekaitan dengan kedudukannya selaku editor yang telah memilih karya-karya yang memang layak dimuat.
Pada hakekatnya makna suatu kritik sastra itu bersifat sangat relatif. Tidak ada seorang kritikus manapun yang bakal bersifat obyektif seratus prosen mengingat begitu banyaknya metode kritik sastra dalam bidang kesusastraan. Pendapat seorang kritikus tidaklah bersifat mutlak benar—apa yang ia tulis hanyalah sebatas buah pikirannya sesuai dengan salah satu metode yang ia gandrungi. Atas dasar inilah mengapa sering terjadi kasus : berapa orang kritikus bertengkar masalah nilai sebuah karya sastra tertentu. Suatu pertengkaran yang disebut polemik di mana tidak ada pakar sastra yang bakal mampu menjadi hakim atau minimal melerai alias mendamaikan perang pena tersebut.
Menguak karya-karya cerpen, novel dan puisi, pada hakekatnya kita mencoba mengungkap dunia misteri berhubung terdapat banyak aliran penulisan yang semuanya dapat disederhanakan menjadi tiga katagori : aliran bersifat transparan dan yang prismatis dan satu lagi yang bersifat silhuet/abstrak. Dengan kalimat lain : karya sastra itu tidaklah seragam. Berangkat dari kenyataan ini maka kita tak menjadi heran; bahwa pihak penyair ( Goenawan Mohamad, Sapardi Joko Damono misalnya ) yang kok tidak mampu menjelasterangkan isi dari sajak-sajak yang digubahnya. “Apa gunanya saya menulis puisi apabila isinya dapat diuraikan secara prosais !” cetus Goenawan Mohamad dalam salah satu esainya. Begitu pula halnya cerpen, secara garis besar terdapat tiga aliran sesuai dengan gaya perintisnya masing-masing : Anton Chekov, Guy de Maupassant dan Franz Kafka.
Meskipun makna suatu kritik sastra relatif sifatnya, kehadiran kritisi sastra adalah penting : para penyair dan pengarang memperoleh hikmah dari kritik sastra yang mereka tulis, berkenaan dengan perkayaan wawasan seputar penciptaan karya sastra, paling tidak para sastrawan dilecut kesadarannya untuk memahami teori sastra maupun sejarah perkembangan kesusastraan dunia sehingga bakat alam yang dimiliki akan bergandengan dengan intelektualisme. Dua komponen yang seyogianya digenggam oleh seseorang yang berpredikat penyair atau pengarang. Berkat pemilikan intelek selaku intelektual maka seseorang di samping menciptakan karya sastra, masing-masing nantinya bakal mampu pula nimbrung dalam polemik dalam bingkai upaya meletakan suatu masalah pada proporsinya yang benar. Atas dasar inilah mengapa dalam bidang kritik sastra hadir isitilah “kritik atas kritik” : suatu pembelaan diri yang positif dari pihak penyair/pengarang yang buah karyanya dikritik baik secara langsung maupun tak langsung.
Sedangkan di dalam buku antologi cerpen terhimpun sejumlah cerpen yang masing-masing punya keunikan tersendiri dan ditopang oleh gaya bercerita (style) yang cukup memikat sesuai dengan tuntutan karya prosa : mengarang fiksi adalah suatu seni bercerita
CERPEN
Putu Arya Tirtawirya
ANGIN LAUT
Jejak langkah kami di pasir yang basah semakin panjang. Sebagian telah terhapus oleh lidah ombak yang menggapai pantai. Dan apakah lagi yang mesti kuucapkan kalau semua telah kubeberkan seperti kartu-kartu terbuka berserakan di depan matanya? Jadi aku cuma melangkah dan melangkah dan mendengar kemerduan suaranya yang membungkus makna kalimat-kalimat yang dilontarkannya. Perempuan memang aneh, teramat kaya akan perbendaharaan bahan percakapan apabila ia telah menaruh percaya terhadap seorang lelaki dan lebih aneh lagi ia akan lantas bungkam kalau kita menutup telinga pada omongan-omongannya yang sepele, — baginya semua adalah sama penting dan patut didengarkan!
“Rambutmu semestinya sudah dicukur,”ujarnya sambil melangkah dan melirik kepadaku.
“Aku belum pernah punya uang,”jawabku dengan nada seloroh.
Wening tertegun kemudian menunduk membuka dompet kulitnya dan sebuah cermin bundar sebesar uang logam ringgit Belanda tampak berkilap memantulkan cahaya matahari sore. Dan aku memandangi renda blouse putihnya di arah liontin emasnya dan berpikir betapa sehat anakku nanti karena bundanya memiliki payudara yang subur. Rupanya, Wening tahu apa yang tengah kupikirkan, dia ketawa seraya mengulurkan tangan kanan.
“Matamu seperti orang yang tak pernah melihat perempuan saja. Nih untuk ongkos cukur!”
Aku ikut ketawa dan memasukkan uang yang disodorkannya ke dalam saku bajuku sambil melangkah lagi menyusuri pantai.
“Sekali tempo ingin aku mentraktirmu, Wening. Kemarin aku menerima honorarium tapi habis kubayarkan langganan majalah…Ayo kita ke situ,”kataku sambil menuding sebuah pohon ketapang yang rindang di atas pasir kering.
Aku melemparkan pantat di atas pasir dan bersandar di batang pohon ketapang itu. Dan Wening membungkukkan tubuhnya sejenak, memeriksa bersih tidaknya pasir yang akan didudukinya. Liontinnya berayun dengan lambannya sejenak. Aku lalu menyapukan pasir yang diperiksanya itu dengan tangan sambil berpikir : alangkah banyaknya seorang wanita punya bagian-bagian tubuh yang bersex-apeal.
“Honor cerpenmu yang mana kau terima kemarin ?” tanya Wening datar sambil mengeluarkan sebungkus jajan dari tas plastiknya yang putih. Aku lalu menjengkau sebuah onde-onde.
“Entahlah, aku belum tahu. Naskah-naskah cerpenku numpuk di majalah itu. Pada strook wesel tak disebutkan cerpenku yang mana. Sayang aku tidak berlangganan majalah tersebut. Gajiku akan habis di majalah saja kalau semua majalah harus kulanggani.”
“Tidak dikirimi nomor bukti ?” celetuknya dengan menggigit pisang goreng dengan giginya yang putih seperti nasi itu.
Suara tawaku ke luar dari hidung.”Redaksi rupanya menganggap para pengarang iseng-iseng menulis cerpennya. Jadi persetanlah mengirimi aku nomor bukti,”jawabku dengan sedikit mangkel.
“Ayok pisang gorengnya,”Wening menggeser bungkus jajan dari kertas itu”Cepatnya lembek, —tadi masih panas-panas kita beli.”
Pisang goreng tanpa diiris. Pisangnya itu kuambil sebuah dan kemudian sengaja kusentuhkan sejenak ke ciincin Wening sebelum kumasukkan ke mulut. Wening yang sedang bersitumpu dengan tinju yang dihiasi cincin pakai permata mirah lantas memukulku kemudian menatapku dengan wajah jenaka.
“Tak kusangka kau nakal, ya!”
Wajah segera kupalingkan kea rah laut. Air laut, elang laut dan perahu nelayan, —semuanya mengingatkan aku pada “The Old Man and The Sea,”—nya Ernest Hemingway.”Wening,”ujarku perlahan tanpa menoleh ke arahnya.
“Apa!”, jawabnya dengan nada seloroh.
Aku terpaksa menoleh ke arahnya. Wening sedang melap bibirnya dengan setangan. Mataku terpaku sejenak pada tahilalat dekat hidungnya.”Kalau kita kawin bulan depan gimana,” tanyaku datar dan tanpa kaku-kaku.
Wening menatap laut yang terhampar di depan kami: beberapa orang lelaki dan perempuan dewasa melintas ke Utara sambil menoleh ke arah kami. Dan matahari sore du tiga jengkal terpacak di atas horizon laut.
“Bagaimana,”ujarku lagi seraya menjengkau onde-onde sebesar buah salak itu lagi.”Gaji kita masa tidak cukup untuk biaya hidup yang sederhana.”
Wening cuma mengejapkan mata, kutahu pandangannya tidak acuh pada panorama laut yang terbentang di depannya.”Apakah kita tidak terlalu muda untuk kawin ?”cetusnya tiba-tiba.
“Kau delapan belas dan aku dua puluh satu, —terlalu muda bagaimana maksudmu ?”
“Mengapa kau cepat-cepat mau kawin ?”ujarnya lagi dengan polos.
“Biar cepat tidur di sampingmu!”, kataku dalam hati. Aku mengetawai kenaifannya mengajukan pertanyaan itu.
“Ajip Rosidi toh kawin di bawah dua puluh,”kataku pasti dan tegas.
“Soalnya, aku takut kehilangan kau, Wening!”
Wening berpaling dan mengerutkan dahinya yang dijumbai oleh anak rambut yang berkibar pelan. “Aku akan lari ke mana sih!”, katanya dengan tegas pula. Nada selorohnya dalam berkata itu makin mempercantik wajahnya dalam pandangan mataku. Dan gelora darah mudaku menyebabkan aku beringsut mendekatinya lalu menopangkan jemari tangan ke pundaknya.
“Aku percaya padamu Wening. Tapi apa yang perlu kita tunggu lagi ? Rumah aku sudah punya. Perabot rumah tangga cuma tinggal melengkapinya saja. Kita sudah bekerja, —walau misalnya kau berniat berhenti kerja, kurasa penghasilanku takkan membingungkan kita. Wening, aku, —aku terlalu mencintaimu.”
“Ah dilihat orang nanti kak!”, Wening menggelinjang ketika tengkuknya yang putih itu kucium dan dia stengah meronta sewaktu bahunya kutarik ke belakang dan mengecup bibirnya yang mungil itu.
Pemberontakannya menyadarkan diriku yang tengah dilingkupi nafsu, bahwa kami tidak berada di tempat sepi. Seperti per, tubuhnya melantun kembali ke depan seperti semula. Wangi bedak dan aroma keringat wanita tambah tak menyabarkan hatiku untuk cepat-cepat melangsungkan perkawinan.
“Bagaimana Wening ?” tanyaku sambil memperbaiki letak blousenya di bagian punggungnya. Dan Wening bangkit seraya mengibaskan roknya dengan pelan, menjatuhkan butir-butir pasir yang melekat.
“Ayok habiskan jajan itu, kemudian mari kita pulang,”jawabnya, menyimpang dari arah pertanyaanku yang pokok.
Sisa jajan kubungkus kembali dan kutolong memasukannya ke dalam tas. Dan tatkala melangkah ke tepi laut, kami lihat pasangan-pasangan yang tampak melintas beberapa waktu yang lalu ke Utara kini telah balik kembali sonder menoleh ke arah kami. Jejak-jejak kaki mereka kami tumpuki dengan jejak kakikku bersama Wening yang berjalan gontai di belakang mereka itu.
Debur ombak masih terdengar sayup sewaktu kami tiba di pintu pekarangan. Kedua orang tua Wening biasanya duduk-duduk di teras rumah kala senja. Tapi tak tampak mereka sewaktu kami melangkah di halaman depan.
“Ayoklah duduk dulu,”kata Wening sambil melangkah ke atas teras.
“Ah tak usah,”jawabku seraya beranjak ke samping rumah untuk mengambil sepeda.
“Yo!”, cetus Wening, ia tertegun di depan tembok teras memandang sayu ke arahku. “Pulang ?”
“Mana orang tuamu ?”kataku sambil menuntun sepeda Phoenix. “Sampaikan salam pamitku pada beliau.”
Wening turun lagi ke halaman menghantarku sampai di pintu halaman. Sambil melangkah aku merogoh saku baju kemudian mengacungkan selembar ribuan yang ia berikan tadi di pantai.”Aku cuma ingin mengujimu, Wening. Semua uang yang selama ini kau berikan tak pernah kupakai,” kataku sambil menyandarkan sepeda di pinggang dan merogoh saku belakang pantalon. Sebuah amplop bekas amplop-retour salah satu cerpenku aku keluarkan dan kuperlihatkan padanya, betapa penuh berisi uang.
“Semuanya adalah uangmu,Wening. Kuharap kau mau menerimanya kembali. Dan barangkali besok aku tak sempat ke mari. Aku akan menghadiri upacara perkawinan seorang temanku sekerja….”
Tapi Wening tidak mau menerima uangnya itu.”Aku sungguh kecewa sekali, ternyata kau tak menggunakan uang pemberianku. Kau telah membuatku sedih, justru menjelang perkawinan kita….sebulan lagi katamu tadi ?” Mata Wening yang hitam itu menatapku tajam-tajam dengan keseriusan yang tak kuduga sama sekali. Darahku seolah tersentak mendengar ucapannya yang terakhir itu dan krasakan kejapan kelopak mataku tambah cepat dar biasa.
“Wening! Kau telah membahagiakan aku senja ini. Baiklah, biar kuhabiskan nanti di hari Minggu, —kupakai mentraktirmu!”, ujarku sambil ketawa. Dan Wening ikut ketawa dan melambaikan tangan.
***
1984
CERPEN
Putu Arya Tirtawirya
GIGI
Dalam bingkai menyajikan topik dunia perdukunan di tanah air, selaku koresponden aku diberikan tugas menelusuri kehidupan orang-orang (“siapa & apa”) yang mengecimpungi ilmu hitam alias black magic di wilayah liputan beritaku. Dan kami kemalaman di kampung pinggiran hutan Pinus tersebut.
“Kita nginap saja di sini—siapa tahu ada tambahan-tambahan bahan yang anda butuhkan”, bisik teman yang mengetahui “peta” kelurahan wilayah setempat. Aku setuju dan kami pada akhirnya mengangguki tawaran tuan rumah, sang dukun, yang menyarankan kami jangan pulang.
Pria tua yang gondrong dan kurus kerempeng itu telah mengontak beberapa orang tetangga—para teman akrabnya—agar mereka datang ngobrol-ngobrol sambil minum tuak dengan sedak gorengan daging kera. Sore tadi pembantunya, seorang pria pendek gempal dengan rambut agak gondrong, berhasil menangkap dua kera besar dalam ladang ketela yang terletak di belakang rumah. Rumah yang beratap genteng-bambu menghadap lembah yang dipencari kampung-kampung. Rumah-rumah penduduk pada beratap genteng-bambu—cocok dengan kondisi cuaca yang boleh dikatakan saban hari turun hujan meskipun tidak lebat. Dan rumah Pak Dukun berlatarbelakang hutan Pinus yang dijejali semak belukar serta aneka pepohonan kecil yang digelayuti kera-kera.
“Kedua kera itu sedang berusaha mencabut batang ketela dengan kedua tangannya di arah punggung ketika saya pergoki…Tumben saya mengalami ada binatang yang bisa juga terkena seputer”, pria pendek itu memberi penjelasan padaku sebelum dia berangkat melaksanakan perintah mengontak tetangga.
Menurut keterangan temanku, seputer merupakan salah satu kekuatan ilmu hitam. Pekarangan yang berisi seputer menyebabkan maling yang masuk bakal mondar-mandir melulu—kena pukau dan tidak menemukan jalan kembali pulang. Begitu pula kera-kera yang tertangkap itu, konon mereka tidak mampu melarikan diri. Mereka mondar-mandir saja dalam ladang ktela. Kemudian menyerah.
“Setahu anda binatang bisa juga kena seputer ?”, tanyaku.
“Baru kali ini aku mendengarnya. Biasanya pencuri-pencuri malam hari kena seputer….”, jawab temanku seraya meranjak ke rumpun pisang. Kencing.
Kamar tamu yang cukup luas dibenderangi sinar lampu stormking merek Kupu-kupu. Sejumlah tikar-pandan tergelar di lantai. Dan kami semua duduk melingkar meghadapi jerigen-jerigen penuh tuak, gelas-bambu serta piring-piring yang penuh goregan daging kera. Aromanya semerbak gurih—barusan digoreng untuk keduakalinya biar disantap sebagai sedak tuak. Pun ada piring besar berisi pelecing kangkung. Ada piring-piring berisi gorengan kacang tanah. Dan sajian lain berupa ketela pohon yang direbus. Putih gembur, uap panasnya masih mengepul dan melayang bercampur asap-asap rokok.
Jam demi jam berlalu dan pengaruh alkohol sadapan bunga-enau tersebut mulai berperan. Aku yang tidak terbiasa minum tuak, beberapa gelas-bambu berhasil kukosongkan—isinya mengguyur kerongkongan dan tergenang dalam usus besar. Denyut-denyut di kepala lambat laun mengikis sikap pemaluku yang berlebihan—keterangan-keterangan yang telah kuperoleh dari dukun-dukun lain aku lontarkan pada hadirin terutama pada Pak Dukun yang mulai teller. Aku minta pendapat beliau. Seperti dakocan milik anakku, Pak Dukun ketawa terkekeh-kekeh sambil tubuhnya oleng ke depan dan ke belakang. Memberi tanggapan maupun jawaban dengan tidak lupa menyelipkan komentar-komentar mendeskriditkan dukun-dukun lain. Tampak dia teramat memitoskan sang ayah, almarhum, yang telah menurunkan ilmu padanya. Sang ayah yang meninggal setahun yang lalu—kena sambaran petir sewaktu menghadapi tugas jadi pawang hujan. Dikalahkan oleh lawan yang ingin meredakan sang hujan. Keterangan ini tentunya tidak keluar dari mulutnya, informasi kuperoleh dari orang lain sebelum aku mengunjunginya siang tadi.
Orang-orang sekitarku tampak ramah-ramah berkat sikapku yang ringan mengangguk mengiyakan maupun terpana oleh setiap ocehannya. Aku dan temanku merupakan figur pendengar yang baik. Aku tidak mau mencari musuh, apalagi statusku sebagai wartawan yang mau tak mau mesti mengorek informasi sebanyak mungkin. Dan aku menyadari, tamu yang duduk sebelah kiriku yang berkumis tebal yang senantiasa menenggak tuaknya secara tuntas kemudian basa-basi menawari teman-teman lain sebelum dirinya menuangi gelas bambunya sendiri, dia sengaja bertanya pada tuanrumah sekedar menambah informasi diriku tentang apa yang pernah dia dengar. Perihal kesaktian almarhum yang berkaitan dengan skandal istri muda beliau tempohari.
Dan tuanrumah dengan gaya khasnya mengekeh-ngekeh kemudian mengisahkan kembali peristiwa tragis tersebut. Sang ibu tiri, istri muda almarhum diam-diam menjalin hubungan cinta dengan pria dari kampung sebelah yang rupanya mampu menggiringnya ke pengalaman orgasmus. Suami sendiri yang berusia begitu tua rupanya tidak memberinya kepuasan seksual. Cuma memberinya ilmu untuk pintar jadi leak—mengubah wujud diri jadi binatang mana suka : babi, kera, anjing, kucing dan sebagainya. Dan kebetulan pria yang diajaknya berkencan itu adalah calon dukun yang sedang mendalami ilmu hitam. Entah bagaimana, suatu malam di bawah sinar bulan di ladang belakang rumah, dua ekor kera jantan dan betina tampak sedang asyik bersetubuh. Hal itu disaksikan oleh almarhum yang kencing di tempat terlindung di belakang rumah. Dan dia mengetahui kera-kera itu bukanlah binatang biasa tapi….yang betina adalah sang istri mudanya sendiri.! Gelora kemarahan melingkupi dirinya dan langsung mengutuk keduanya agar tetap jadi kera. Mereka terkejut dan melarikan diri ke dalam hutan. Dan peristiwa tersebut diungkapkan oleh sang ayah menjelang menghembuskan nafas terakhir, setahun yang lampau.
Berjam-jam duduk bersila, lantaran tak biasa duduk bersila lama-lama menyebabkan sekujur kakiku pegal-pegal dan ditambah lagi keinginan kencing yang sengaja kutahan-tahan menunggu selesainya tuanrumah berkisah.
Aku cepat-cepat permisi ke belakang, akan kencing. Dan dalam perjalanan kurang lebih sepuluh meter menuju tempat pembuangan sampah, pikiranku bergalau. Mana kepala berat berdenyut-denyut akibat alkohol kampungan yang bernama tuak, kemudian dirong-rong pertanyaan tak terjawab seputar misteri hilangnya kedua insan yang berbeda jenis kelamin tersebut. Apa iya ? Pun melintas-lintas dalam benakku keunikan masyarakat setempat—para lelaki warga kampung semuanya gemar mengunyah sirihpinang. Gigi mereka sehat-sehat tetapi dironai merah kehitaman. Hanya kalangan anak-anak dan muda remaja yang bergigi putih-putih. Minum tuak dan mengunyah sirihpinang sudah membudaya.
Seekor anjing tua berbulu putih kotor tampak berada di atas tumpukan sampah. Dia menoleh sejenak ke arahku kemudian dia tidak ambil peduli pada kehadiranku. Sambil mengangkang aku mendongak memandang bulan sepotong di langit. Tiba-tiba sekujur tubuhku merinding. Aku menolehi sekitar tapi tidak ada apa-apa. Mungkin akibat kebanyakan minum tuak. Mataku memandang sang anjing. Dia asyik menjilati dan mengerkah sesuatu. Ingin tahu menyebabkan aku memperhatikan dengan cermat apa yang dimakannya. Ternyata kepala kera. Tuan rumah membantai dua ekor kera. Digoreng. Kepala kera yang satu lagi tampak tergeletak tidak jauh dari ekor anjing putih itu—bersandar di ember plastik hijau yang rusak. Kembali kurasakan sekujur tubuh merinding. Mata kupejamkan seraya menggelengkan kepala dengan maksud melenyapkan sejenak pengaruh alkohol. Apakah mataku tidak salah lihat ? Sepintas seperti ada wajah wanita cantik di arah ember plastic rusak tersebut. Dan begitu mataku terbuka kulihat kepala kera biasa.
Mata kualihkan ke kepala kera yang sedang dikerkah sang anjing. Tiba-tiba perutku mual dengan hebatnya—gigi anjing mencabik-cabik bibir kera itu dan….diterangi sinar bulan tampak gigi-gigi sang kera berwarna merah kehitaman!!
Membludak isi ususku ke luar. Muntah hebat. Aku mencari pegangan di batang pohon kelor, tidak jauh dari tempatku kencing.
“Kenapa?!....kenapa ?!”
Temanku rupanya mau kencing pula, dia menyusulku. Dia kaget dan cepat memijit tengkukku. Dia tidak tahu persoalan.
Aku muntah lagi sambil merentangkan tangan ke arah sang anjing.
“Kera itu bukan kera tulen!”
Dan tidak lama berselang kudengar dia ikut muntah hebat pula.
****
Horison/XXIV/602/1990